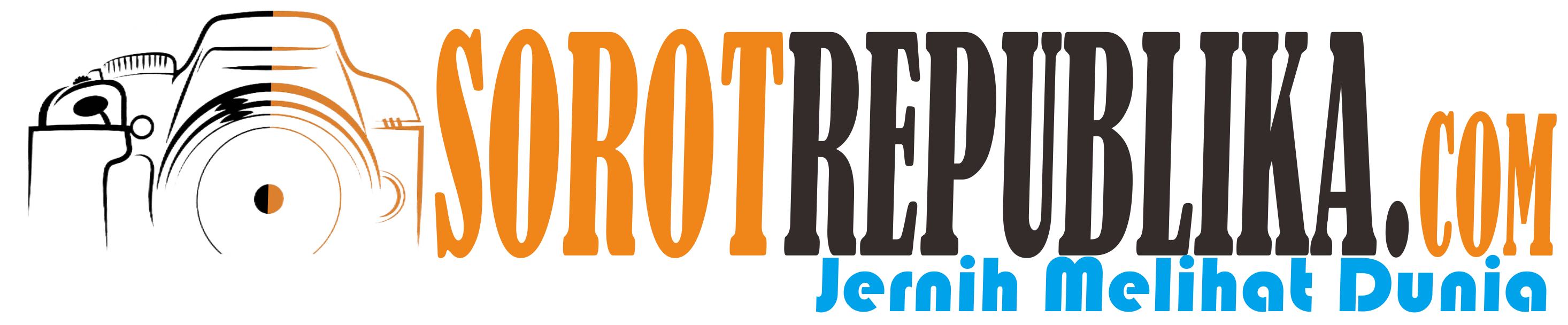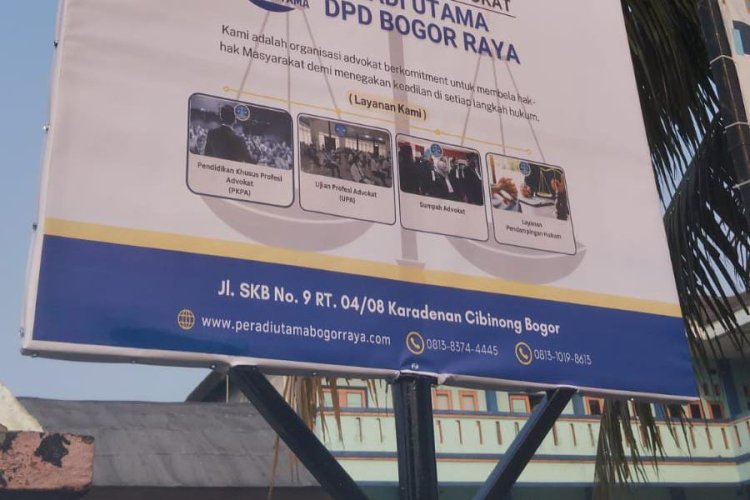Aceh Singkil | Lebih dari dua minggu sejak banjir bandang meluluhlantakkan Aceh dan sebagian wilayah Sumatera, penanganannya justru menampilkan absurditas khas republik ini, dimana negara yang lebih rajin meredam kritik ketimbang mengurus korban. Di tengah lumpur, pengungsian, dan ratusan jenazah yang dievakuasi, publik disuguhi drama demi drama yang seolah dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan utama, yakni lambatnya respons dan absennya kepemimpinan bencana. Jumat (12/12/25).
Kisah itu bermula ketika Kepala BNPB menyebut banjir Aceh “tak parah” seperti yang ramai di media sosial. Pernyataan itu langsung dibakar kritik publik. Di lapangan, ribuan warga terjebak, jembatan rubuh, ratusan kilometer jalan terputus, dan listrik padam berhari-hari. Ketika tekanan meningkat, Kepala BNPB akhirnya meminta maaf, sebuah pola klasik ketika negara tidak siap, tetapi tetap berusaha terlihat menguasai keadaan.
Desakan agar bencana Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional semakin lantang. Sejumlah negara, termasuk para pengusaha diaspora Aceh di Malaysia, menyampaikan kesiapan membantu tetapi terkendala status. Namun pemerintah pusat tetap bersikukuh bahwa Aceh masih “mampu menangani sendiri”. Klaim itu janggal jika melihat data di lapangan dan seruan keputusasaan dari daerah-daerah terdampak.
Beberapa kabupaten bahkan mengirim surat pernyataan ketidaksanggupan. Belakangan terungkap surat itu merupakan arahan Pemerintah Provinsi. Namun alih-alih digunakan untuk mengusulkan status bencana nasional, Gubernur Aceh Muzakir Manaf justru menuding para bupati “cengeng” dan tak mampu bekerja.
Drama kian melebar ketika Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang ikut menandatangani surat ketidaksanggupan itu, viral karena berangkat umrah tanpa izin gubernur. Pemerintah Aceh baru menyampaikan penolakan izinnya ketika sang bupati sudah dalam perjalanan menuju Makkah. Kejadian itu langsung menjadi konsumsi politik nasional bahkan Ketua Komisi II DPR dari Nasdem mengecam keras, Mendagri turun tangan, Gerindra memecat Mirwan dari jabatan partai, Presiden Prabowo menyindir keras, hingga akhirnya status nonaktif dijatuhkan kepada Mirwan MS.
Belum reda, muncul pula episode “93 persen listrik menyala”. Di hadapan Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim pemulihan listrik Aceh telah mencapai 93 persen. Warga Aceh yang malam itu gelap gulita membalas klaim tersebut dengan banjir kritik. Beberapa hari kemudian Bahlil meminta maaf, sementara Dirut PLN mengklarifikasi bahwa sistem kelistrikan Aceh sedang gagal sinkronisasi dan diperkirakan baru pulih 14 Desember.
Rangkaian drama itu menyita energi publik. Namun justru celah inilah yang paling mengkhawatirkan. Serangkaian kegaduhan seakan menenggelamkan isu pokok yang semestinya menjadi fokus negara, kenapa penanganan begitu lambat, apa akar penyebab banjir sebesar ini, dan mengapa pemerintah pusat begitu menolak menetapkannya sebagai bencana nasional? Dalam lanskap politik dan ekonomi yang rumit, persoalannya tampak lebih dari sekadar “harga diri bangsa”.
*Di Balik Penolakan Bencana Nasional: Ekologi yang Terkoyak*
Secara objektif, hampir seluruh indikator bencana nasional terpenuhi. Walhi Aceh menegaskan sedikitnya lima variabel utama yaitu korban besar, pengungsian masif, kerusakan infrastruktur, wilayah terdampak luas, dan pemerintah daerah kewalahan. Data BNPB membenarkan kondisi itu. Per 8 Desember 2025, korban meninggal mencapai 974 orang, 298 hilang, dan puluhan ribu mengungsi. Angka-angka itu terus bergerak naik.